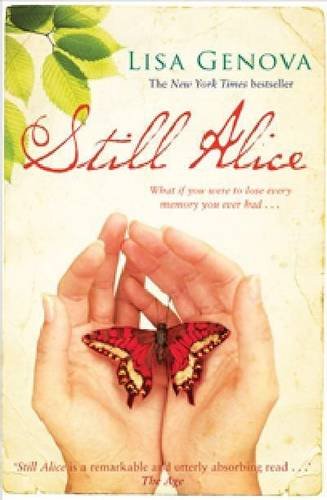Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Desember 2011
ISBN: 9792278125 (ISBN13: 9789792278125)
“Baru kusadari bahwa aku tidak datang membawa mimpi ataupun aspirasi. Aku tidak ingin jadi apa-apa. Aku cukup puas berbaring terlentang di atas ranjang sambil menatap langit-langit kosong. Aku seperti pelampung yang mengapung di atas permukaan laut luas dan terkatung-katung tanpa arah; menelan perguliran hari dan malam tanpa henti seolah aku abadi.”
Nicky F. Rompa adalah seseorang yang mungkin kita kenal dalam kehidupan sehari-hari; lelaki biasa yang hidupnya lurus-lurus saja, tanpa punya keinginan dan harapan akan masa depan. Karena ingin kabur dari ayahnya yang kasar, ketika kesempatan untuk pindah ke Amerika datang, dia ambil dengan harapan bahwa dia bisa menemukan aspirasi dan keinginannya di sana. Meninggalkan Ibu dan Shanaz, adiknya, dan Reno, sahabatnya.
Di Amerika, Nicky tinggal bersama keluarga tantenya, Tante Riesma. Sebagai pendatang di sebuah negeri yang asing dan megah, di mana jutaan orang dari seluruh dunia menggantungkan mimpi, Nicky perlahan-lahan beradaptasi dan bertahan. Nicky bertemu dengan orang-orang yang luar biasa menarik dan berasal dari latar belakang yang menunjukan betapa multikurturalnya Amerika. Yang pertama adalah Mr. & Mrs. Wong, imigran asal Vietnam pemilik toko serba ada di mana Nicky pertama kali bekerja. Leah sepupunya dan pacarnya, Richard Klaus. Polina, gadis Rusia bermata hijau yang tidak bisa Nicky lupakan dari awal bertemu. Dev Akhtar, pemuda Pakistan yang berpacaran dengan Natalie Black, seorang gadis Yahudi. Artin Rucci, guru menulis Nicky yang meyakinkan Nicky bahwa dia bisa menjadi penulis hebat kalau dia tekun. Esmeralda de Luca Garcia – Esme – kekasih Nicky yang berasal dari Meksiko.
Winter Dreams adalah buku berisi 287 halaman tentang perjalanan hidup seseorang di negeri orang, yang mungkin terlihat simpel dan membosankan karena tidak ada plot maupun konflik yang menggebu-gebu. Nicky menjalankan hidupnya sebagaimana sebagian besar dari kita menjalani hidup; berteman dengan orang-orang lalu kehilangan kontak dengan mereka, pacaran lalu putus, bersenang-senang, mencoba sesuatu yang baru dan berbahaya, berhenti dari satu pekerjaan untuk bekerja di tempat lain, jatuh cinta dengan pasangan sahabat sendiri, lalu patah hati. Tidak mengerti dengan masa lalu dan masa depan seolah-olah semua itu ilusi. Menjalani hari ini tanpa sesuatu yang berarti. Segala kebosanan ini terdengar familiar dengan kita, bukan? Karena begitulah hidup. Kadang kalau kita beruntung, kita tumbuh menjadi seseorang yang penuh semangat, memiliki keseharian yang luar biasa menarik dengan pengalaman-pengalaman yang bisa membuat banyak orang lain iri. Tapi sering kali, kita tidak seberuntung itu. Kita cuma tokoh anti-hero yang kalau kisah hidupnya dibukukan, mungkin hanya akan muat sampai 50, 75 halaman. Di buku ini Maggie tidak berusaha untuk mencekoki kita dengan ilusi, fantasi tentang mimpi-mimpi muluk, tapi dia hanya ingin menunjukan bahwa ketika muda, merasa bingung itu wajar. Tidak punya harapan, juga wajar. Dan ketika punya harapan tapi tidak kesampaian, ya apa boleh buat. Kita cuma punya dua pilihan: duduk dan menghabiskan sepanjang masa muda dan masa depan kita berfikir bahwa kita bisa merubah hidup, atau bangkit dan benar-benar membuat perubahan. Bahwa “Life has a strange sense of humor and sometimes God makes up for it by working in mysterious ways,” dan “Waktu berlalu. Banyak hal yang akan berubah. Hidup akan terus bergulir seperti mimpi.”
Dengan prosa yang memukau, detil yang kaya, dan karakter yang warna-warni, Maggie berhasil membungkus kisah Nicky menjadi sesuatu yang mengikat kita dalam pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita berpikir dan merefleksikan diri, apakah selama ini kita sudah cukup bermimpi? Apakah kita sudah cukup mengenal diri kita?
4/5 bintang.
Nicky F. Rompa adalah seseorang yang mungkin kita kenal dalam kehidupan sehari-hari; lelaki biasa yang hidupnya lurus-lurus saja, tanpa punya keinginan dan harapan akan masa depan. Karena ingin kabur dari ayahnya yang kasar, ketika kesempatan untuk pindah ke Amerika datang, dia ambil dengan harapan bahwa dia bisa menemukan aspirasi dan keinginannya di sana. Meninggalkan Ibu dan Shanaz, adiknya, dan Reno, sahabatnya.
Di Amerika, Nicky tinggal bersama keluarga tantenya, Tante Riesma. Sebagai pendatang di sebuah negeri yang asing dan megah, di mana jutaan orang dari seluruh dunia menggantungkan mimpi, Nicky perlahan-lahan beradaptasi dan bertahan. Nicky bertemu dengan orang-orang yang luar biasa menarik dan berasal dari latar belakang yang menunjukan betapa multikurturalnya Amerika. Yang pertama adalah Mr. & Mrs. Wong, imigran asal Vietnam pemilik toko serba ada di mana Nicky pertama kali bekerja. Leah sepupunya dan pacarnya, Richard Klaus. Polina, gadis Rusia bermata hijau yang tidak bisa Nicky lupakan dari awal bertemu. Dev Akhtar, pemuda Pakistan yang berpacaran dengan Natalie Black, seorang gadis Yahudi. Artin Rucci, guru menulis Nicky yang meyakinkan Nicky bahwa dia bisa menjadi penulis hebat kalau dia tekun. Esmeralda de Luca Garcia – Esme – kekasih Nicky yang berasal dari Meksiko.
Winter Dreams adalah buku berisi 287 halaman tentang perjalanan hidup seseorang di negeri orang, yang mungkin terlihat simpel dan membosankan karena tidak ada plot maupun konflik yang menggebu-gebu. Nicky menjalankan hidupnya sebagaimana sebagian besar dari kita menjalani hidup; berteman dengan orang-orang lalu kehilangan kontak dengan mereka, pacaran lalu putus, bersenang-senang, mencoba sesuatu yang baru dan berbahaya, berhenti dari satu pekerjaan untuk bekerja di tempat lain, jatuh cinta dengan pasangan sahabat sendiri, lalu patah hati. Tidak mengerti dengan masa lalu dan masa depan seolah-olah semua itu ilusi. Menjalani hari ini tanpa sesuatu yang berarti. Segala kebosanan ini terdengar familiar dengan kita, bukan? Karena begitulah hidup. Kadang kalau kita beruntung, kita tumbuh menjadi seseorang yang penuh semangat, memiliki keseharian yang luar biasa menarik dengan pengalaman-pengalaman yang bisa membuat banyak orang lain iri. Tapi sering kali, kita tidak seberuntung itu. Kita cuma tokoh anti-hero yang kalau kisah hidupnya dibukukan, mungkin hanya akan muat sampai 50, 75 halaman. Di buku ini Maggie tidak berusaha untuk mencekoki kita dengan ilusi, fantasi tentang mimpi-mimpi muluk, tapi dia hanya ingin menunjukan bahwa ketika muda, merasa bingung itu wajar. Tidak punya harapan, juga wajar. Dan ketika punya harapan tapi tidak kesampaian, ya apa boleh buat. Kita cuma punya dua pilihan: duduk dan menghabiskan sepanjang masa muda dan masa depan kita berfikir bahwa kita bisa merubah hidup, atau bangkit dan benar-benar membuat perubahan. Bahwa “Life has a strange sense of humor and sometimes God makes up for it by working in mysterious ways,” dan “Waktu berlalu. Banyak hal yang akan berubah. Hidup akan terus bergulir seperti mimpi.”
Dengan prosa yang memukau, detil yang kaya, dan karakter yang warna-warni, Maggie berhasil membungkus kisah Nicky menjadi sesuatu yang mengikat kita dalam pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita berpikir dan merefleksikan diri, apakah selama ini kita sudah cukup bermimpi? Apakah kita sudah cukup mengenal diri kita?
4/5 bintang.