“I love you as certain dark things are loved, secretly, between the shadow and the soul.” - Anna and the French Kiss
Jujur saja, ketika teman-teman dari BBI sepakat untuk membaca satu buku romance bersama di bulan ini, saya kelimpungan. Saya tidak punya buku romance yang belum terbaca! Setelah mengubek-ngubek rak buku selama beberapa menit, mata saya menangkap satu judul buku.
"Anna and the French Kiss". Judul ini saat itu seolah dikelilingi lampu-lampu kecil yang bersinar-sinar, seperti tulisan di sebuah pementasan kabaret. *lebay*
Kaver bukunya yang menampilkan seorang model perempuan yang sedang tersenyum manis, hendak meraih tangan seorang pria di sebelahnya yang wajahnya tak nampak, dengan tampilan separuh menara Eiffel sebagai background dan judul yang provokatif membuat saya yakin bahwa ini akan menjadi satu bacaan yang manis. Terlebih lagi, ada banyak sekali review positif dari buku ini yang bertebaran di Goodreads atau blog-blog buku.
Lima sampai sepuluh halaman pertama, saya masih belum mengerti mengapa buku ini mendapat perhatian sedemikian rupa. Plotnya sangat sederhana, tipikal malah:
Anna Oliphant "dikirim" oleh ayahnya ke Paris untuk melanjutkan tahun terakhir SMA-nya di sana; padahal dia sudah punya segudang rencana untuk menghabiskan tahun ini di Atlanta bersama sahabatnya, Bridge, dan pacarnya Toph. Dia sama sekali tidak tertarik akan Paris dan segala keromantisannya, malahan dia takut akan merasa kesepian, kangen rumah, dan tidak punya teman di sana. Dengan segala kekhawatirannya, dia berangkat ke Prancis, tanpa tahu satupun kata dalam Prancis - kecuali Merci - sambil membawa kekesalan besar pada ayahnya.
Tapi segalanya berubah saat dia akhirnya masuk ke SOAP (School of America in Paris) yang didaftarkan Ayahnya, sekolah elit yang dipenuhi beraneka ragam orang di sana. Tak disangka dia dengan mudah berteman dengan Meredith, Rashmi, Josh dan Ettiene St.Clair, cowok Inggris tampan yang diidolakan banyak cewek di sekolahnya.
Akhirnya bisa ditebak, bukan? Anna naksir St.Clair, St.Clair naksir Anna, lalu mereka berciuman di bawah Menara Eiffel. The end.
Plotnya, meskipun simpel, tetap saja tidak sesimpel tulisan asal saya di atas. Meski kisah mereka memang happy ending - cover semanis ini kalau ceritanya tidak happy ending rasanya keterlaluan - tapi tetap saja, penuh liku. Tapi yang menjadi poin plus buku ini, dan memang inilah alasan mengapa banyak orang menyukainya, adalah: cerita dan karakternya begitu realistis. Tidak ada perpisahan dramatis, atau kematian yang mengharu biru. Semuanya berjalan dengan smooth dan santai, tapi Stephanie dengan apik meramu cerita yang terdengar klise menjadi sesuatu yang tidak membosankan. Tidak ada ledakan emosi yang meluap-luap atau sub-plot yang berlebihan. Rasanya seperti mendengar curhatan teman yang lama tidak dijumpai. Rasanya nyata.
Karakter-karakternya juga menyenangkan. Tidak seperti karakter novel yang melewati banyak hal seru sampai-sampai kita ingin sekali menjadi temannya di dunia nyata, tapi lebih seperti teman yang ceritanya dibukukan lalu kita baca. Dari semua karakter, tentu saja karakter favorit saya Etienne St.Clair. Perlu tanya lagi yah? Dia pintar, sayang banget sama Mamanya, dan dia BRITISH. Need I say more?
Dan satu lagi aspek penting dari buku ini yang tak boleh ketinggalan dibahas: romance. Sebagai orang yang tidak terlalu suka buku romance, saya sangat puas dengan kadar romance di buku ini. Pas! Tidak lebih, tidak kurang. Sangat realistis, menurut saya. Saya paling suka bagian saling berbalas e-mail di buku ini. Manis sekali :)
All in all, buku ini cocok untuk dibaca ketika sedang suntuk dan ingin membaca buku ringan dan cepat habis, setelah lama membaca buku-buku yang topiknya bikin puyeng, ditemani segelas minuman hangat dan cuaca yang gloomy, supaya bisa semangat lagi!
4/5 stars.
Monday, October 31, 2011
Sunday, October 30, 2011
Hans Christian Andersen, Penulis Dongeng Abadi
Hans Christian Andersen adalah salah satu dari sekian banyak pengarang cerita anak-anak yang masih sering dibicarakan hingga hari ini. Berbagai karangannya sudah bisa dinikmati dalam banyak versi, mulai dari film, kartun, maupun drama panggung. Beberapa kisah Andersen yang tidak asing di telinga kita yakni Thumbelina, Putri Duyung, Gadis Penjual Korek Api, hingga Si Itik Buruk Rupa. Bila ditanya siapa pengarang favorit saya waktu kecil, jawabannya mudah: Hans Christian Andersen. Saya membaca dongeng-dongengnya ketika saya baru masuk SD, bahkan bisa dibilang saya mengoleksi semua buku dongengnya yang diterbitkan Gramedia. Sayang, buku-buku itu sudah rusak karena banjir di rumah saya beberapa tahun yang lalu.
Saya begitu menyukai dongeng-dongengnya karena mereka sangat berbeda dari dongeng-dongeng pada umumnya, yang biasanya berkisah tentang tokoh-tokoh cantik, atau yang hidupnya berakhir bahagia. Cerita-cerita yang ditulis Hans Christian Andersen malah sebaliknya, bernuansa gelap, kelam, magis. Kisah Gadis Penjual Korek Api adalah kisah favorit saya hingga kini.
Kisah-kisah kelam yang dituangkan Andersen sedikit banyak diimbaskan dari masa kecilnya yang menyedihkan. Dibesarkan dari keluarga miskin, sejak belia Andersen diharuskan untuk menjadi buruh kasar untuk menambah penghasilan keluarga. Bahkan, dari kecil hingga dewasa, Andersen tidak pernah memiliki rumah - sepanjang hidupnya, ia hidup di rumah para tokoh masyarakat yang kaya raya, atau tinggal di kamar sewaan dengan perabot minim. Sejak dirinya menjadi penulis, banyak pengagum karyanya yang memperbolehkan Andersen tinggal beberapa lama di rumahnya.
Karena bekerja itulah, Andersen tidak mendapat pendidikan yang seharusnya. Dari hasil keberuntungan dia seuatu ketika bertemu dengan Raja Denmark Frederik VI yang tertarik dengan penampilannya dan lalu membiayai dia sekolah bahasa. Dia terlambat beberapa tahun sebelum akhirnya mulai bersekolah, dan ini membuat dirinya rendah diri di antara anak-anak yang jauh lebih muda darinya, belum lagi penyakit disleksia yang dia idap membuatnya jadi korban olok-olok. Menurutnya, kurun waktu sekolah adalah masa-masa paling kelam dan menyakitkan dalam hidupnya. Setelah beberapa tahun, akhirnya Andersen lulus dari sekolah bahasa. Dia lantas melanjutkan studinya di Universitas Kopenhagen, dengan dibiayai oleh seorang pemilik teater bernama Jonas Collin. Di tahun-tahun kuliahnya ini, dia mulai menulis beberapa cerita dan puisi. Andersen juga menulis drama musik anak-anak yang lantas dipentaskan di teater milik Jonas Collin.
Sampai di akhir hidupnya, Andersen tidak pernah menikah. Mirip seperti kisah Putri Duyung yang ditulisnya, dia sempat jatuh cinta pada seorang gadis namun bertepuk sebelah tangan. Dia meninggal tahun 1874 setelah digerogoti berbagai penyakit selama sekian tahun.
Every man’s life is a fairy tale, written by God’s fingers, begitulah kutipan perkataannya yang terkenal hingga saat ini. Dengan menulis, dia bisa menciptakan suatu kehidupan baru, yang dia tulis sedemikian rupa hingga menjadi indah. Dia bisa menuangkan luapan kepahitan dan kesedihannya. Karya-karyanya yang sarat akan kenyataan hidup dan tidak mengumbar "keindahan palsu" mencerminkan ketulusan perasaannya. Dan hal inilah yang meninggalkan bekas di hati para pembacanya, memberikan makna pada kehidupan banyak orang di dunia. Kisah-kisahnya tak pernah lekang oleh waktu.
Saya begitu menyukai dongeng-dongengnya karena mereka sangat berbeda dari dongeng-dongeng pada umumnya, yang biasanya berkisah tentang tokoh-tokoh cantik, atau yang hidupnya berakhir bahagia. Cerita-cerita yang ditulis Hans Christian Andersen malah sebaliknya, bernuansa gelap, kelam, magis. Kisah Gadis Penjual Korek Api adalah kisah favorit saya hingga kini.
Kisah-kisah kelam yang dituangkan Andersen sedikit banyak diimbaskan dari masa kecilnya yang menyedihkan. Dibesarkan dari keluarga miskin, sejak belia Andersen diharuskan untuk menjadi buruh kasar untuk menambah penghasilan keluarga. Bahkan, dari kecil hingga dewasa, Andersen tidak pernah memiliki rumah - sepanjang hidupnya, ia hidup di rumah para tokoh masyarakat yang kaya raya, atau tinggal di kamar sewaan dengan perabot minim. Sejak dirinya menjadi penulis, banyak pengagum karyanya yang memperbolehkan Andersen tinggal beberapa lama di rumahnya.
Karena bekerja itulah, Andersen tidak mendapat pendidikan yang seharusnya. Dari hasil keberuntungan dia seuatu ketika bertemu dengan Raja Denmark Frederik VI yang tertarik dengan penampilannya dan lalu membiayai dia sekolah bahasa. Dia terlambat beberapa tahun sebelum akhirnya mulai bersekolah, dan ini membuat dirinya rendah diri di antara anak-anak yang jauh lebih muda darinya, belum lagi penyakit disleksia yang dia idap membuatnya jadi korban olok-olok. Menurutnya, kurun waktu sekolah adalah masa-masa paling kelam dan menyakitkan dalam hidupnya. Setelah beberapa tahun, akhirnya Andersen lulus dari sekolah bahasa. Dia lantas melanjutkan studinya di Universitas Kopenhagen, dengan dibiayai oleh seorang pemilik teater bernama Jonas Collin. Di tahun-tahun kuliahnya ini, dia mulai menulis beberapa cerita dan puisi. Andersen juga menulis drama musik anak-anak yang lantas dipentaskan di teater milik Jonas Collin.
Sampai di akhir hidupnya, Andersen tidak pernah menikah. Mirip seperti kisah Putri Duyung yang ditulisnya, dia sempat jatuh cinta pada seorang gadis namun bertepuk sebelah tangan. Dia meninggal tahun 1874 setelah digerogoti berbagai penyakit selama sekian tahun.
Every man’s life is a fairy tale, written by God’s fingers, begitulah kutipan perkataannya yang terkenal hingga saat ini. Dengan menulis, dia bisa menciptakan suatu kehidupan baru, yang dia tulis sedemikian rupa hingga menjadi indah. Dia bisa menuangkan luapan kepahitan dan kesedihannya. Karya-karyanya yang sarat akan kenyataan hidup dan tidak mengumbar "keindahan palsu" mencerminkan ketulusan perasaannya. Dan hal inilah yang meninggalkan bekas di hati para pembacanya, memberikan makna pada kehidupan banyak orang di dunia. Kisah-kisahnya tak pernah lekang oleh waktu.
Saturday, October 22, 2011
Paper Towns - John Green
When I finished reading Looking For Alaska, I eventually thought that I finally found the perfect kind of characters that I would dyingly (it doesn't even a word) see alive.
After reading Paper Towns, I thought to myself, "MAN, I WAS WRONG! Paper Towns is definitely the best book of John Green that I've ever read!!"
Not that I've read all of his books, actually.
The plot evolves around Quentin or more likely to be called Q, who has fallen in love with his neighbor Margo ever since he was a kid. One day they found a dead body at a park near their houses, and that discovery impacts differently on both of them. Q only thought that it was nothing to be seriously thinking about, but Margo eventually wonders how fragile life is as she grows up. Margo has never been the same.
"Margo always loved mysteries. And in everything that came afterward, I could never stop thinking that maybe she loved mysteries so much that she became one."
Even though Q has known Margo for years, he still can not understand her.
She has become a mystery. A paper girl. A Margo persona that Margo only wants to project. Margo is a popular girl next door (literally) and Q is just a geek.. Then one night Margo shows up at Q's window, looking for help to lead a wondrous night full of rebel, revenge--Margo as the ninja with blue spray paint, catfish and Veet, with Q as his sidekick.
Q totally thinks that his time finally comes. He can start to understand her. He can show her that he is not a loser kinda geek that people may think.. But then she disappears. No, not just for hours or 2 days or 3 days. For weeks.
Q has all kinds of speculation. What if she ends up in a damp in the middle of nowhere? What if she was kidnapped? Or worse, what if she kills herself, and her body is nowhere to be found?
But Q believes that Margo left some clues to him. And it's his job to find her.
Paper Towns is not an ordinary young adult book. It is full of geekyness and depths and metaphors and quirky people and jokes and sadness and depression. And I really love this book because of that. I actually could read the book within a day but no, I didn't do it because I didn't want this book to end.
What I liked about this book is its characters. Margo is a depressed young girl who is too fed up with all the hypocrisy of people around her. Margo leads on this night of revenge with Q because her boyfriend cheats on her and she thinks her friends around her already know that fact--but still betray her. She is fed up with the whatnots on the future,and all about it is just a repetition; she will graduate high school, she will have a job, she will get married, have babies, have grandchildren, and she will die. She wants to live freely without wanting to know what's gonna happen tomorrow.
Q is the exact opposite of Margo. He is smart, everything about his future is no longer a stressful thing to think about. But he doesn't have the nerve to live in spontaneity and he wonders why is that.
Radar is a genius and reliable, whose parents owns the biggest collection of Black Santas in the world. Ben is a typical funny guy and everything that comes out of his mouth makes me laugh. Lacey is.. a girl.
The last thing I loved from this book:
“Maybe its like you said before, all of us being cracked open. Like each of us starts out as a watertight vessel. And then things happen - these people leave us, or don’t love us, or don’t get us, or we don’t get them, and we lose and fail and hurt one another. And the vessel starts to crack in places. And I mean, yeah once the vessel cracks open, the end becomes inevitable. Once it starts to rain inside the Osprey, it will never be remodeled. But there is all this time between when the cracks start to open up and when we finally fall apart. And its only that time that we see one another, because we see out of ourselves through our cracks and into others through theirs. When did we see each other face to face? Not until you saw into my cracks and I saw into yours. Before that we were just looking at ideas of each other, like looking at your window shade, but never seeing inside. But once the vessel cracks, the light can get in. The light can get out.”
After reading Paper Towns, I thought to myself, "MAN, I WAS WRONG! Paper Towns is definitely the best book of John Green that I've ever read!!"
Not that I've read all of his books, actually.
The plot evolves around Quentin or more likely to be called Q, who has fallen in love with his neighbor Margo ever since he was a kid. One day they found a dead body at a park near their houses, and that discovery impacts differently on both of them. Q only thought that it was nothing to be seriously thinking about, but Margo eventually wonders how fragile life is as she grows up. Margo has never been the same.
"Margo always loved mysteries. And in everything that came afterward, I could never stop thinking that maybe she loved mysteries so much that she became one."
Even though Q has known Margo for years, he still can not understand her.
She has become a mystery. A paper girl. A Margo persona that Margo only wants to project. Margo is a popular girl next door (literally) and Q is just a geek.. Then one night Margo shows up at Q's window, looking for help to lead a wondrous night full of rebel, revenge--Margo as the ninja with blue spray paint, catfish and Veet, with Q as his sidekick.
Q totally thinks that his time finally comes. He can start to understand her. He can show her that he is not a loser kinda geek that people may think.. But then she disappears. No, not just for hours or 2 days or 3 days. For weeks.
Q has all kinds of speculation. What if she ends up in a damp in the middle of nowhere? What if she was kidnapped? Or worse, what if she kills herself, and her body is nowhere to be found?
But Q believes that Margo left some clues to him. And it's his job to find her.
Paper Towns is not an ordinary young adult book. It is full of geekyness and depths and metaphors and quirky people and jokes and sadness and depression. And I really love this book because of that. I actually could read the book within a day but no, I didn't do it because I didn't want this book to end.
What I liked about this book is its characters. Margo is a depressed young girl who is too fed up with all the hypocrisy of people around her. Margo leads on this night of revenge with Q because her boyfriend cheats on her and she thinks her friends around her already know that fact--but still betray her. She is fed up with the whatnots on the future,and all about it is just a repetition; she will graduate high school, she will have a job, she will get married, have babies, have grandchildren, and she will die. She wants to live freely without wanting to know what's gonna happen tomorrow.
Q is the exact opposite of Margo. He is smart, everything about his future is no longer a stressful thing to think about. But he doesn't have the nerve to live in spontaneity and he wonders why is that.
Radar is a genius and reliable, whose parents owns the biggest collection of Black Santas in the world. Ben is a typical funny guy and everything that comes out of his mouth makes me laugh. Lacey is.. a girl.
The last thing I loved from this book:
“Maybe its like you said before, all of us being cracked open. Like each of us starts out as a watertight vessel. And then things happen - these people leave us, or don’t love us, or don’t get us, or we don’t get them, and we lose and fail and hurt one another. And the vessel starts to crack in places. And I mean, yeah once the vessel cracks open, the end becomes inevitable. Once it starts to rain inside the Osprey, it will never be remodeled. But there is all this time between when the cracks start to open up and when we finally fall apart. And its only that time that we see one another, because we see out of ourselves through our cracks and into others through theirs. When did we see each other face to face? Not until you saw into my cracks and I saw into yours. Before that we were just looking at ideas of each other, like looking at your window shade, but never seeing inside. But once the vessel cracks, the light can get in. The light can get out.”
Still Alice - Lisa Genova
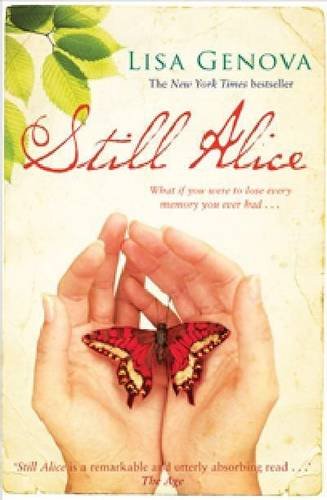 Pernah dengar tentang penyakit Alzheimer's?
Pernah dengar tentang penyakit Alzheimer's? Kalau pernah nonton film Korea berjudul A Moment To Remember yang dibintangi Son Ye Jin dan Jung Woo Sung - atau film The Notebook yang dibintangi Ryan Gosling dan diangkat dari buku karya Nicholas Sparks berjudul sama, mungkin Alzheimer's Disease bukanlah satu nama yang asing di telinga.
Alzheimer's Disease adalah suatu kondisi di mana sel-sel otak yang menyimpan memori - baik memori lama maupun baru - sudah tidak berfungsi dengan baik. Banyak orang yang salah kaprah mengira Alzheimer's sama saja dengan pikun, padahal tidak begitu.
Bayangkan; kamu seorang profesor yang hebat di Harvard, baru berumur 50 tahun, memiliki tiga anak yang sudah dewasa dan suami yang sukses. Seharusnya saat ini kamu sedang menikmati bagaimana enaknya kerja sebelum pensiun, menunggu rasanya menimang cucu. Inilah waktumu menikmati hidup.
Alice Howland adalah seorang profesor sukses di bidang Psikologi di Harvard berusia 50 tahun. Kehebatannya sebagai dosen sudah tidak usah ditanyakan lagi - selain sering diundang menjadi dosen tamu di seluruh dunia, dia juga menjadi dosen favorit di Harvard. Mengajar tentang psikologi kognitif atau psikolinguistik? Dia bisa menyiapkannya hanya dalam waktu 5 menit, dengan otaknya yang luar biasa cerdas.
Ketika awalnya dia tidak bisa mencari padanan kata yang tepat ketika mengajar, dia mengira ini dampak dari menopause. Ketika BlackBerry-nya tertinggal di sebuah restoran, dia merasa ini masih wajar. Tapi saat suatu kali dia tidak bisa mencari jalan pulang ketika sedang jogging, atau waktu dia benar-benar lupa bahwa dirinya harus mengajar di Chicago, dia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Ada apa denganku?
Dunianya terasa jungkir balik saat diagnosa dokter datang. Alzheimer's. Dia masih akan lebih bersyukur bila dia terkena tumor otak - setidaknya ada satu hal yang bisa dia perjuangkan, satu monster yang akan dengan sekuat tenaga berusaha dia kalahkan. Ada secercah harapan bahwa suatu saat dia akan menang. Namun Alzheimer's? Ini jenis penyakit yang akan terus dia bawa seumur hidup. Dia hanya bisa terus menerus minum obat, tak punya kendali atas masa depannya sendiri, menunggu kapan tiba waktunya dia mulai melupakan bagaimana caranya makan, mandi, berbicara. Siapa suami dan anak-anaknya. Bahkan dirinya sendiri.
Ini bukan buku yang sempurna atau terbaik. Banyak sekali ketimpangan prosa di sana-sini; ada beberapa paragraf yang terasa terlalu ilmiah, seolah-olah kita sedang membaca sebuah esai kedokteran. Di sisi lain, penulis menceritakan tentang suatu hal dengan penuh metafora, hingga rasanya terlalu berlebihan. Tapi ketika kita menutup mata atas segala kekurangannya, baru kita bisa melihat betapa hebatnya buku ini. Semua karakter berkembang di waktu yang tepat - hanya saja menurut saya porsi Tom terlalu kurang - tidak ada sub-plot membingungkan, dan ceritanya mengalir dengan pas. Pilihan penulis untuk memakai sudut pandang ketiga juga sangat brilian. Benar-benar buku yang emosional dan tidak bisa dilupakan begitu saja.
Buku ini tidak cocok dibaca kalau sedang sedih dan ingin membaca buku yang ringan dan cepat selesai.
Subscribe to:
Posts (Atom)



